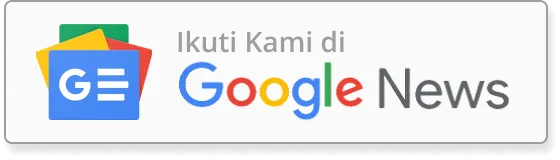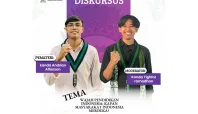Mimbartimur.com – Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentang optimalisasi 273 ribu hektare lahan Areal Penggunaan Lain (APL) tampak seperti langkah maju dalam pengelolaan aset negara. Namun di balik bahasa pembangunan yang indah, publik perlu memahami secara jernih: optimalisasi tanah untuk siapa, dan dengan cara seperti apa?
Ketika Gubernur Maluku Utara menyebut 273 ribu hektare lahan siap dioptimalkan untuk sektor hilirisasi seperti kelapa, cengkeh, dan pala, angka itu terdengar menjanjikan. Tetapi di lapangan, lahan bukan sekadar hektare di atas kertas. Di balik setiap hektare, ada hak masyarakat adat, lahan garapan rakyat, dan ekosistem hidup yang berlapis sejarah sosial.
Penting untuk diingat bahwa tanah di Maluku Utara bukan hanya aset ekonomi, tapi juga ruang hidup dan identitas budaya. Kesalahan umum dalam kebijakan agraria di berbagai daerah adalah melihat tanah semata dari sudut pandang investasi dan produktivitas, tanpa menimbang dimensi sosial-ekologisnya.
Secara prinsip, Bank Tanah dibentuk untuk menata kembali penguasaan tanah negara agar lebih adil dan efisien. Namun, jika pengelolaan tidak transparan dan partisipatif, kebijakan ini justru bisa melahirkan bentuk baru ketimpangan agraria.
Bank Tanah seharusnya tidak menjadi “bank” bagi modal besar untuk menguasai lahan tidur, melainkan menjadi penjamin keadilan distribusi tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan atau petani kecil yang membutuhkan kepastian hak. Dalam konteks ini, publik berhak menuntut agar setiap langkah optimalisasi lahan harus:
Berbasis data spasial yang terbuka,
Melibatkan masyarakat lokal dan adat dalam pemetaan dan memastikan tidak ada penggusuran terselubung atas nama investasi.
Kata “hilirisasi” sering disebut dalam pidato pembangunan daerah, tapi jarang dijabarkan dalam konteks kesejahteraan petani. Jika kerja sama Bank Tanah dan Pemprov Maluku Utara hanya berhenti pada penyediaan lahan untuk investor besar, petani lokal hanya akan menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Pembangunan seharusnya tidak hanya mengundang modal, tetapi juga membangun kapasitas lokal — koperasi tani, akses pupuk, riset bibit unggul, dan pasar yang adil. Di sinilah makna sejati dari “optimalisasi tanah” bukan seberapa cepat lahan digarap, tapi seberapa luas kesejahteraan rakyat yang terwujud.
Maluku Utara memiliki sejarah panjang soal konflik lahan — dari izin tambang hingga proyek perkebunan. Karena itu, kerja sama antara Pemprov dan Bank Tanah harus diawasi secara publik, bukan hanya disorot sebagai keberhasilan administratif. Pemerintah perlu memastikan setiap hektare tanah yang dioptimalkan mengandung nilai keadilan, keberlanjutan, dan transparansi.
Jika Bank Tanah menjadi instrumen redistribusi yang adil dan berpihak pada rakyat, maka MoU ini bisa menjadi tonggak perubahan positif. Tetapi jika justru membuka ruang baru bagi akumulasi modal dan pengabaian hak masyarakat, maka yang terjadi bukan optimalisasi, melainkan reproduksi ketimpangan dalam wajah baru.
Kebijakan pertanahan yang baik adalah kebijakan yang berakar pada keadilan sosial dan berpijak pada partisipasi rakyat. Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih punya peluang untuk membuktikan bahwa pembangunan tidak selalu berarti komersialisasi tanah, melainkan pengelolaan ruang hidup yang menyejahterakan manusia dan menjaga alam. ***
Muhammad Laskar Alting
Anak Muda Kota Tidore Kepualuan