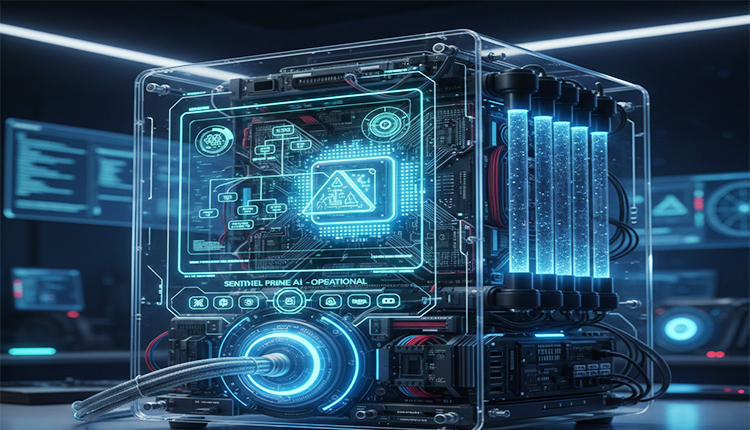Bahasa media sosial membentuk jaringan perbedaan yang sangat tajam. Value sebuah kata kini bergantung pada konteks, platform, dan kepada siapa ia diarahkan. Makna tunggal pun runtuh, digantikan oleh makna-makna fragmentaris yang hanya dapat dipahami oleh suku-suku tribalisme digital tertentu.
Matinya makna tunggal membawa konsekuensi sosial yang mahal. Jika dahulu bahasa berfungsi sebagai alat untuk saling memahami, kini ia kerap berubah menjadi tembok pemisah. Masalahnya bukan lagi pada apa yang kita katakan, melainkan pada siapa yang mendengarnya. Fragmentasi makna menjebak komunikasi kita dalam filter bubble dan ruang gema.
Ironinya, kita sering menggunakan penanda yang sama, tetapi di kepala masing-masing muncul petanda yang sama sekali berbeda. Ketika kata keadilan atau kebebasan dilempar ke kolom komentar, bagi satu kelompok ia adalah aspirasi moral, bagi kelompok lain justru provokasi ideologis. Kita tidak lagi berdebat tentang gagasan, melainkan saling menyerang karena gagal menyepakati sistem tanda yang relatif stabil.
Di titik ini, kritik sosial paling tajam adalah hilangnya empati linguistik. Kita semakin malas memahami konteks orang lain karena merasa paling berhak atas makna sebuah kata. Bahasa yang menurut Saussure bersifat kolektif, kini diprivatisasi oleh ego kelompok. Akibatnya, yang lahir bukan diskusi sehat, melainkan cancel culture dan penghakiman massal, hanya karena perbedaan tafsir atas tanda yang sejatinya manasuka.
Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, kita sedang menuju “Menara Babel” versi modern. Kita berbicara dengan bahasa yang sama, tetapi tak seorang pun benar-benar memahami maksud orang di sebelahnya.
Pada akhirnya, Ferdinand de Saussure tidak hanya mewariskan teori tentang bagaimana kata bekerja, melainkan juga cermin untuk membaca denyut masyarakat. Media sosial memang telah meruntuhkan otoritas makna tunggal, menjadikannya cair, liar, dan kerap tak terkendali. Namun barangkali inilah saatnya kita menyadari bahwa bahasa memang tidak pernah menjadi benda mati di dalam kamus. Ia adalah organisme hidup yang bernapas melalui interaksi sehari-hari.
Mempelajari Saussure di tengah riuh algoritma hari ini memberi kita satu pelajaran penting: setiap tanda yang kita lempar ke ruang publik membawa tanggung jawab sosial. Jika hubungan antara penanda dan petanda bersifat manasuka, maka kitalah yang memilih, apakah kemanasukaan itu digunakan untuk membangun pemahaman, atau justru memperlebar jurang kebencian.
Matinya makna tunggal seharusnya bukan alasan untuk berhenti berkomunikasi. Sebaliknya, ia adalah undangan untuk bersikap rendah hati: lebih banyak mendengar konteks sebelum menghakimi teks. Di dunia yang semakin bising, kemampuan untuk menyepakati makna sekecil apapun atau setidaknya saling memahami perbedaannya adalah bentuk perlawanan paling nyata terhadap perpecahan. Kita mungkin tak lagi memiliki satu makna yang mutlak, tetapi kita selalu bisa memilih untuk menjaga satu empati yang utuh.
Penulis : Nahda Auliana – Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMMU
***