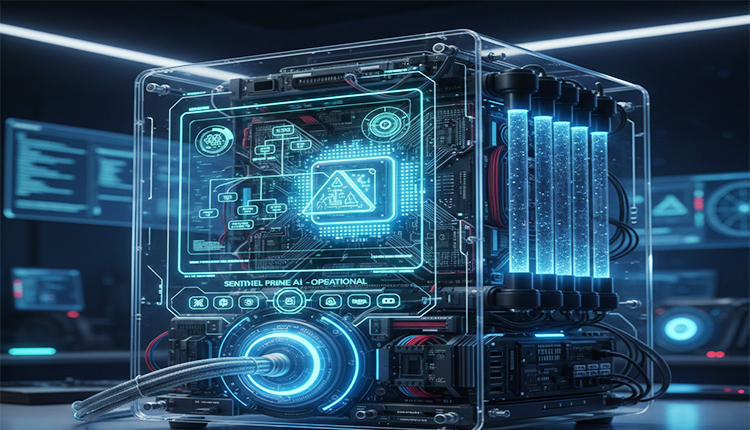“Tulisan ini merupakan tugas pengganti Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi yang ditugaskan oleh dosen pengampu M. Nofrizal Amir, dengan tujuan menganalisis pemikiran Ferdinand de Saussure dalam konteks realitas sosial dan digital manusia hari ini”.
Belum lama ini, jagat media sosial diramaikan oleh istilah skena. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini memang belum menemukan rumah yang mapan. Namun dalam praktik komunikasi digital, skena justru hidup subur sebagai label subkultur dengan gaya hidup, selera, dan identitas yang sangat spesifik. Ia bukan sekadar kata, melainkan penanda keanggotaan sosial.
Fenomena serupa juga tampak pada penggunaan emoji. Emoji menangis, misalnya, secara harfiah melambangkan kesedihan. Namun di tangan Generasi Z, simbol ini justru dimaknai sebagai tawa terbahak-bahak, rasa gemas yang berlebihan, atau ekspresi ironi. Tangis yang berubah menjadi tawa. Di sinilah kita melihat satu gejala penting, bahwa di era digital, makna tidak lagi tunggal dan statis.
Gejala “liarnya” makna ini sesungguhnya telah diramalkan Ferdinand de Saussure (1916), bapak linguistik modern, lebih dari satu abad lalu. Melalui prinsip arbitrariness, Saussure menegaskan bahwa hubungan antara bentuk bunyi atau tulisan (penanda) dan konsep (petanda) bersifat manasuka, tidak alamiah, melainkan hasil kesepakatan sosial. Bahasa, dengan demikian, bersifat cair. Bedanya, jika dahulu pergeseran makna berlangsung perlahan secara diakronik, membutuhkan puluhan tahun, maka kini media sosial mempercepatnya hanya dalam hitungan jam, bahkan menit.
Dalam tulisan ini, saya berupaya membedah bagaimana algoritma dan budaya internet secara perlahan membunuh otoritas makna tunggal. Dengan meminjam kacamata Saussure, kita dapat melihat bahwa komunikasi di media sosial bukan lagi soal mencari kebenaran di dalam kamus, melainkan soal bagaimana tanda-tanda dinegosiasikan, diperebutkan, dan direbut kembali di tengah riuh arus informasi.
Dalam teori Saussure, tanda linguistik adalah kesatuan antara signifiant (penanda) dan signifié (petanda). Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan ini relatif stabil. Namun di media sosial, relasi tersebut menjadi rapuh. Ambil contoh istilah red flag. Secara sinkronik, ia berarti bendera merah atau tanda bahaya. Tetapi di ruang digital, istilah ini mengalami perluasan makna: ia menjadi label bagi sifat atau perilaku bermasalah dalam relasi asmara. Satu penanda, petanda yang sama sekali baru.
Kecepatan pergeseran ini menunjukkan prinsip arbitrariness Saussure pada level yang ekstrem. Makna tidak lagi ditentukan oleh otoritas bahasa seperti KBBI atau para ahli linguistik, melainkan oleh siapa yang paling viral. Ketika sebuah komunitas sepakat bahwa kata Mulyono bukan lagi sekadar nama diri, melainkan simbol politik tertentu, maka makna lama pun tertindih oleh kesepakatan sosial baru yang masif.
Saussure juga membedakan antara langue, sistem bahasa yang baku dan kolektif dan parole, praktik berbahasa individu. Dahulu, langue dianggap sebagai panglima; kita berbicara dengan tunduk pada aturan. Namun media sosial membalik hierarki ini. Parole digital, ucapan spontan, slang, plesetan, dan singkatan di kolom komentar, kini justru lebih berkuasa dalam membentuk realitas bahasa dibandingkan kaidah tata bahasa yang kaku.
Setiap thread di X atau video singkat di TikTok adalah bentuk parole yang terus-menerus mengguncang stabilitas langue. Akibatnya, bahasa tidak lagi tampil sebagai sistem kolektif yang stabil, melainkan sebagai medan tempur identitas yang dinamis dan sering kali agresif.
Lebih jauh, Saussure menekankan bahwa makna lahir dari perbedaan: sebuah kata bermakna karena ia bukan kata yang lain. Di media sosial, prinsip ini berubah menjadi alat polarisasi. Istilah seperti cebong, kampret, woke, atau sigma memperoleh maknanya bukan dari definisi kamus, melainkan dari oposisi terhadap kelompok lain. Bahasa menjadi senjata, bukan jembatan.