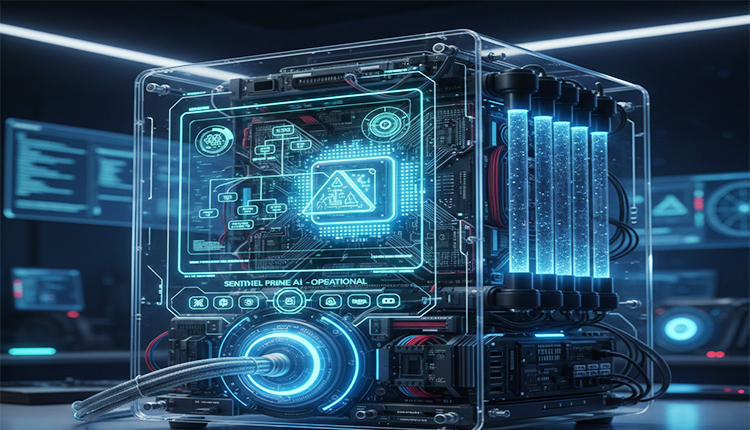“APBD semestinya mengalir ke warga, bukan berhenti di proyek dan papan nama”
Tulisan ini berawal dari refleksi atas begitu banyak proyek infrastruktur fisik yang terbengkalai di Maluku Utara. Jejak pembangunan sering kali berhenti di papan nama proyek. Pelabuhan Feri Doro di Kao Halmahera Utara yang tak berfungsi, sentra IKM di Halmahera Barat yang kosong tanpa aktivitas, hingga pelabuhan perikanan yang terbengkalai di beberapa titik di Halmahera Selatan adalah contoh bahwa anggaran publik tidak otomatis menjadi manfaat publik.
APBD yang mestinya menjadi instrumen kesejahteraan justru sering bertransformasi menjadi simbol pembangunan semu. Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: Anggaran ini sebenarnya untuk siapa
Logika yang Terbalik
Pemerintah daerah kerap mengukur keberhasilan dari seberapa banyak proyek fisik yang bisa ditampilkan. Gedung, jalan, dermaga, atau pasar menjadi alat legitimasi politik paling mudah karena hasilnya terlihat dan bisa diresmikan. Namun orientasi seperti ini melahirkan bias anggaran: proyek fisik disusun bukan karena urgensi publik, tetapi karena mudah dipertanggungjawabkan secara administratif dan menguntungkan secara citra.
Dalam logika seperti ini, keberhasilan dihitung berdasarkan serapan, bukan perubahan sosial. Fasilitas fisik selesai dibangun tetapi gagal berfungsi karena tidak lahir dari kebutuhan warga. Yang tinggal hanyalah infrastruktur yang menganggur, menjadi monumen dari kegagalan perencanaan.
Anggaran yang Kehilangan Makna Publik
Dalam kerangka keuangan publik, APBD memikul fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Idealnya, anggaran daerah harus memperkuat layanan dasar: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan akses ekonomi bagi rakyat kecil. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Struktur APBD Maluku Utara tahun 2025 menunjukkan bahwa anggaran kehilangan orientasi publiknya. Data tahun berjalan menunjukkan bahwa belanja operasional mencapai lebih dari 2,6 triliun, sekitar 74 persen dari total belanja. Sekilas hal ini tampak wajar, tetapi setelah dibedah, terlihat bahwa belanja barang dan jasa justru lebih besar daripada belanja pegawai. Ini bukan tanda efisiensi, melainkan indikasi bahwa anggaran tersedot ke kegiatan administratif, paket-paket pengadaan kecil, perjalanan dinas, hingga aktivitas rutin yang tidak menghasilkan peningkatan kualitas layanan publik.
Lebih jauh, komponen anggaran yang menyentuh warga justru berada pada posisi paling kecil: belanja subsidi nihil, dan belanja bantuan sosial hanya sekitar enam miliar rupiah. Angka ini tidak berarti apa-apa ketika masyarakat menghadapi tekanan harga, ketimpangan layanan dasar, dan akses ekonomi yang timpang antarwilayah. Padahal fungsi distribusi dan stabilisasi APBD justru berada di ruang ini.
Sementara itu, belanja modal hanya sekitar 528 miliar, atau 15 persen dari total belanja. Namun struktur internal belanja modal memperlihatkan kecenderungan yang sama: lebih dari 80 persen belanja modal diarahkan ke proyek fisik seperti jalan, jaringan, irigasi, gedung, bangunan, serta peralatan dan mesin. Ini paralel dengan temuan di lapangan: pembangunan dikejar sebagai simbol politik, bukan sebagai instrumen pelayanan publik. Infrastruktur lebih sering menjadi target seremonial daripada kebutuhan masyarakat.
Belanja yang seharusnya memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi rakyat—pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal—justru tidak tercermin dalam pola belanja tersebut. APBD akhirnya berjalan dalam dua logika yang saling menguatkan: logika kegiatan dalam belanja operasional dan logika fisik dalam belanja modal. Keduanya jauh dari esensi anggaran publik yang semestinya melindungi dan memperkuat kualitas hidup masyarakat.